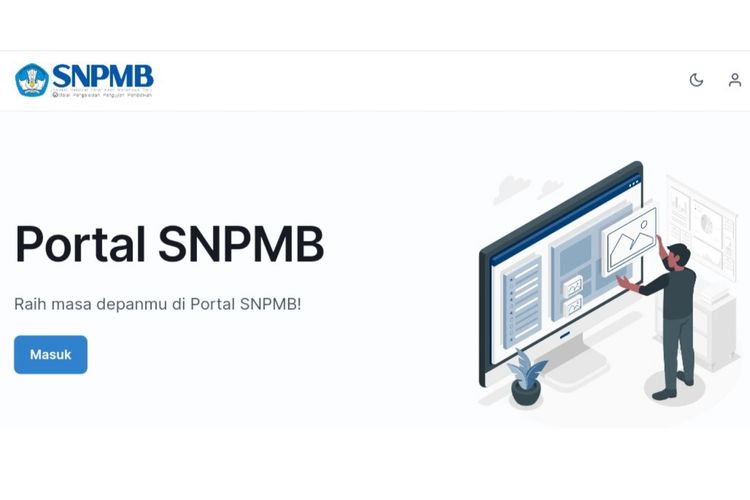SHARE:
Teuku Kemal Fasya
Rosid Hossain (55 tahun) adalah pengungsi terakhir yang menghuni kamp penampungan eks Balai Latihan Kerja (BLK) di Gampong Meunasah Blang Mee, Lhokseumawe pada Agustus 2021. Ia bersama istrinya Rosyida (47 Tahun) dan kedua anaknya Nobi Hossain (20 Tahun) dan Tosmin Ara (21 Tahun) adalah satu-satunya keluarga imigran yang tersisa.
Mereka telah menetap di kamp penampungan selama 1,5 tahun. Sebelum pelarian dan memasuki wilayah Indonesia. Rosid dan keluarga menjadi salah satu kelurga penghuni Kamp Cox’s Bazar, Bangladesh. Mereka menetap selama tiga tahun di sana.
Tidak seperti para pengungsi yang kemudian dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan, Rosid ingin bergabung dengan dua anaknya, Iman Hossain dan Dildar Hossain yang telah berada di Makassar. Alasannya, kehidupan di Makassar lebih baik dibandingkan di Aceh atau Medan. Ketika penulis menggenggamkan sedikit uangnya kepadanya, air matanya langsung tumpah, seolah tak pernah ada bantuan selain dari lembaga penanganan pengungsi.
Elegi pengungsi
Kasus Rosid tidak lagi lumer sebagai kisah etnografis duka pengungsi Rohingya, tapi telah tergulung ke dalam dokumen statistik. Indonesia sendiri menjadi tujuan transit etnis yang dituduh berasal dari Bangladesh itu, meski bukan utama.
Etnis Rohingya sendiri menjadi satu-satunya pengungsi global yang terdampar di Aceh sejak 2009. Telah ada 17 gelombang yang tiba, terakhir sekali pada 6 Maret 2022 di Bireuen dengan jumlah 114 orang. Sejak 2011 telah ada 1.802 orang yang mendarat, sebagian di antaranya ada sakit, meninggal, dan hamil (Kompas.id, 6 Maret 2022). Untuk kasus hamil, ada pola “mensuami-istrikan secara darurat” meskipun bukan pasangan yang sah.
Kisah pendaratan pun kerap berubah dari histeria menjadi disturbia. Awalnya para pengungsi disambut dengan penuh haru oleh masyarakat. Ada situasi ketika pihak TNI-Polri hendak menghalau pengungsi untuk kembali ke laut lepas, para nelayan memasang badan dengan menarik kapal yang bocor rusak itu ke darat. Alasannya klasik, membantu sesama muslim yang dizalimi di negeri lain.
Namun, seperti judul film yang dibintangi Harrison Ford, What Lies Beneath (2000), ada dusta kerap bersembunyi di balik ketulusan, yaitu kasus perdagangan orang (human trafficking). Seperti terlihat kasus penyeludupan 99 pengungsi Rohingya 25 Juni 2020, Pengadilan Negeri Lhoksukon menghukum empat orang termasuk FA, yang berprofesi sebagai nelayan. Kasus FA hanya gunung es tentang penyeludupan manusia yang menurut PBB dianggap the most persecuted minority in the world. Belum lagi kasus pendaratan terakhir di Bireuen, pengungsi Rohingya sempat diusir warga karena menambah beban dan kerap melarikan diri.
Tentang kasus Rohingya kerap melarikan diri dari Aceh bukan cerita baru. Itu karena Indonesia hanya transit memuluskan laluan utama ke Malaysia dan Australia. Bahkan ada pengungsi yang tidak langsung dari Rakhine (Myanmar) atau Cox’s Bazar (Bangladesh), tapi telah tinggal di Malaysia. Hanya karena tertangkap bekerja ilegal mereka diusir dan mendarat ke Indonesa untuk kembali cari peluang masuk ke Malaysia.
Cox’s Bazar adalah gumpalan kompleksitas masalah sendiri. Dengan menampung sedikitnya 750 ribu pengungsi, wilayah Bangladesh itu telah mereplikasi masalah di Myanmar yang berhubungan dengan eksploitasi, kekurangan makanan, akses kesehatan, pendidikan, dan pembatasan. Hasil wawancara penulis dengan penghuni salah satu community house Rudenim di Medan pada 2021, mereka mengeluarkan uang RM 1.500 – 5.000 atau sekitar Rp5-17 juta per orang untuk bisa keluar dari tempat pengungsian terbesar di dunia itu. Uang mereka dapatkan dari penjualan aset di kampung halaman dan “utang” dengan kerabat yang telah tinggal di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Timur Tengah.
Dilema Indonesia
Indonesia sendiri memilih jalan “bijaksana” dengan belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka, apalagi di era resesi ekonomi seperti saat ini. Namun, belum meratifikasi bukan berarti menolak mengambil tanggung-jawab kemanusiaan dan bersikap etis atas masalah warga tak berwarganegara itu (stateless citizens).
Sejak 19 Mei 1975 Indonesia telah menerima “manusia perahu” Vietnam di Kota Tarempa, Kepulauan Riau. Setelah itu bagai air bah para pengungsi Indocina itu masuk ke Batam, Natuna, dan Kuku setiap hari (Missbach, 2015). Hingga kini masih ada 13.343 pengungsi dari 20 negara yang kurang 60 persennya bisa difasilitasi organisasi migrasi internasional, IOM.
Apa yang menyebabkan Indonesia tidak bisa menolak para pengungsi untuk masuk? Seperti falsafah pada pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggungjawab moral untuk mengupayakan perdamaian dunia. Khusus kasus di negara ASEAN, Indonesia terikat konsensus non-intervensi terkait konflik Rohingya, tapi tetap harus pro-aktif menangani masalah tsunami pengungsi. Apalagi “hanya” menangani sekitar 13 ribu pengungsi global, Indonesia kurang dramatis dibandingkan Malaysia (163.600) dan Thailand (97.439) yang berkali lipat menampung manusia tanpa teritori itu (Riyanto, 16 Juni 2022). Meskipun tidak menandatangani Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memberlakukan prinsip non-refoulement dengan tidak pernah mengusir pengungsi kemanusiaan dan rentan dipersekusi oleh negara asal.
Pada masa pemerintahan Jokowi, Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres 125 tahun 2016 dalam penanganan pengungsi. Regulasi ini nama lain dari bentuk penghargaan terhadap Konvensi PBB serta kepedulian Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan pengungsi. Perpres tersebut memberikan 43 pedoman bagi setiap daerah yang menampung pengungsi untuk sementara, seperti yang terjadi di Aceh.
Namun di lapangan, implementasi Perpres Nomor 125/2016 tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ada beberapa hambatan akibat belum dipahaminya regulasi tersebut di tingkat daerah atau tidak tersedia anggaran serta fasilitas untuk menangani pengungsi sesuai ketentuan Perpres. Singkat kata, Perpres itu baru bertindak sebagai respons darurat, tapi belum menjadi solusi komprehensif untuk mereka yang terhina dan terusir dari negaranya itu.
Pada momentum hari pengungsi sedunia (World Refugee Day) yang jatuh pada 20 Juni, kita harus semakin bersiteguh untuk menyelesaikan masalah pengungsi, terutama Rohingya sebagai komitmen menyalakan kemanusiaan tanpa meremehkan benteng perlindungan bangsa dari racun non-nasionalisme.
Teuku Kemal Fasya, Kepala UPT Bahasa, Kehumasan, dan Penerbitan Universitas Malikussaleh. Tahun 2021 menjadi ketua tim riset Dampak Sosial-Ekonomi Pengungsi Rohingya di Aceh dari Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri R.I.
Telah dimuat di Kompas.id, 23 Juni 2022.