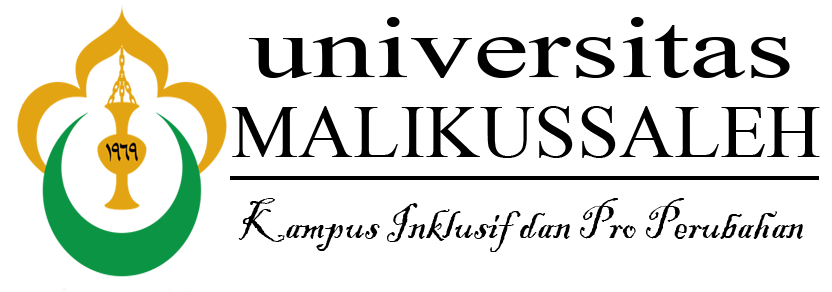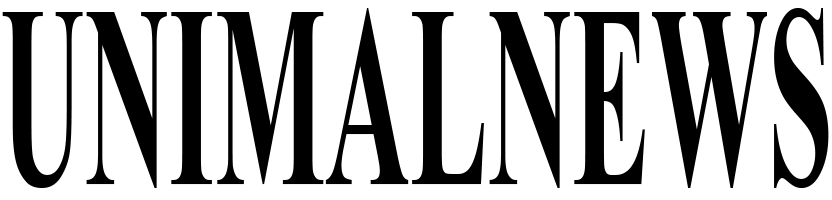SHARE:

BEBERAPA bulan terakhir, jagat media sosial diramaikan dengan berbagai konten viral yang menyematkan istilah-istilah psikologis, salah satunya adalah skizofrenia. Kata ini kerap muncul dalam komentar atau unggahan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap aneh, berbicara sendiri, atau menunjukkan emosi yang ekstrem. Sayangnya, penggunaan istilah skizofrenia dalam konteks yang keliru ini telah menyesatkan publik dan semakin mempertebal stigma terhadap gangguan kejiwaan tersebut.
Padahal, skizofrenia bukanlah sekadar “gila” atau kehilangan akal, tetapi merupakan gangguan mental kompleks yang membutuhkan pemahaman serta penanganan serius. Fenomena ini menjadi cermin betapa minimnya literasi kesehatan mental di tengah masyarakat, yang berdampak besar terhadap penerimaan sosial dan kualitas hidup para penyintas.
Saya meyakini bahwa penyebaran informasi yang salah mengenai skizofrenia dapat berdampak negatif terhadap upaya penanganan dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa di Indonesia. Bukan hanya karena membuat penyintas semakin dikucilkan, tetapi juga karena menimbulkan ketakutan dan kesalahpahaman publik. Oleh sebab itu, opini ini mengajak masyarakat untuk membuka mata dan hati terhadap realitas skizofrenia, meninggalkan stigma lama, serta membangun solidaritas sosial yang lebih manusiawi dalam menghadapi isu kesehatan mental.
Mengenal Skizofrenia dengan Perspektif Ilmiah dan Manusiawi
Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan kronis dan berat yang memengaruhi persepsi, pemikiran, emosi, serta perilaku seseorang. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), skizofrenia ditandai dengan gejala utama seperti halusinasi, delusi, pikiran kacau, dan gangguan fungsi sosial. Penyebabnya multifaktorial, mulai dari ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, faktor genetik, stres lingkungan, hingga trauma masa kecil.
Skizofrenia bukanlah akibat “lemah iman” atau kerasukan seperti yang masih dipercaya sebagian masyarakat tradisional. Banyak penyintas yang, dengan dukungan medis dan sosial yang tepat, mampu menjalani hidup yang produktif dan berdaya. Melabeli mereka sebagai “orang gila” bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga menghambat proses pemulihan mereka.
Stigma Sosial: Luka yang Lebih Dalam dari Penyakit Itu Sendiri
Salah satu tantangan terbesar bagi penderita skizofrenia bukan hanya pada gejala medisnya, melainkan stigma yang menempel kuat di masyarakat. Label-label seperti “berbahaya”, “gila”, atau “tidak waras” membuat para penyintas dijauhi bahkan oleh keluarganya sendiri. Penelitian dari Kemenkes RI tahun 2023 menunjukkan bahwa 1 dari 5 penderita gangguan jiwa berat di Indonesia tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai karena stigma dari lingkungan sekitar.
Tidak jarang pula, mereka dikurung di rumah, dirantai, atau ditelantarkan tanpa perawatan yang layak. Hal ini menunjukkan betapa diskriminatifnya sistem sosial kita terhadap kelompok rentan. Stigma ini menciptakan efek domino: penyintas menjadi takut mencari pertolongan, keluarga merasa malu, dan masyarakat enggan membuka ruang inklusi.
Media Sosial dan Popularisasi Istilah Psikologis: Antara Edukasi dan Sensasionalisme
Media sosial sebenarnya memiliki potensi besar sebagai alat edukasi kesehatan mental, namun kenyataannya, banyak pengguna yang malah mempermainkan istilah psikologis demi konten yang viral. Istilah skizofrenia sering kali dipakai secara sembarangan untuk menyindir atau menjatuhkan orang lain.
Dalam beberapa kasus, bahkan terlihat ada konten video yang menampilkan penderita gangguan jiwa untuk dijadikan hiburan semata. Ini jelas bentuk eksploitasi dan pelanggaran etika. Bukannya membangun kesadaran, konten semacam itu justru menormalisasi diskriminasi dan memperparah pemahaman keliru publik. Padahal, apabila digunakan secara tepat, media sosial bisa menjadi ruang penghubung antara para penyintas, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam memperkuat solidaritas dan empati.
Pentingnya Edukasi dan Dukungan Sosial dalam Menangani Skizofrenia
Skizofrenia adalah gangguan yang bisa dikendalikan melalui pengobatan jangka panjang, terapi psikososial, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Namun, semua ini akan sulit tercapai jika masyarakat masih memandang penderita sebagai beban sosial. Dibutuhkan edukasi yang konsisten dari pemerintah, sekolah, lembaga kesehatan, dan media massa tentang pentingnya mendukung penyintas.
Di banyak negara maju, kampanye kesadaran mental seperti “Time to Change” di Inggris telah berhasil menurunkan stigma terhadap skizofrenia secara signifikan. Indonesia juga harus berani berinvestasi dalam literasi kesehatan mental, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan tenaga profesional agar pesan ini menjangkau lapisan masyarakat luas.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa skizofrenia bukanlah bahan olok-olokan atau simbol kelemahan seseorang, melainkan suatu kondisi medis yang memerlukan penanganan dan empati. Selama stigma masih dibiarkan berkembang, maka penderita skizofrenia akan terus mengalami keterasingan sosial yang menyakitkan.
Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam menciptakan ruang yang inklusif, bukan justru memperkuat sekat-sekat yang memisahkan mereka dari kehidupan normal. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan mental. Mari hentikan penggunaan istilah psikologis sebagai lelucon, dan mulai ubah narasi kita menjadi lebih peduli, menghargai, dan membantu sesama. Karena memahami skizofrenia bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal kemanusiaan.[]
Penulis : Mishkatul Ameerah, mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh